Cerpen Ali Syamsudin Arsi
Selintas. Selembar daun gugur.
“Telah berpuluh lembar memeluk humus di kesuburan, tanah ini menerima. Penerimaan yang tulus dan sabar,” Lelaki Atas Dirinya berniat mempersunting Gadis Pelangi yang duduk termangu, antara desah di bulu-bulu halus permukaan daun. “Akh, kau, pasti ada yang berdegup dalam detak jantungmu dan seperti biasa bagian bawah bibirmu akan bergerak kecil untuk mengatakan sesuatu yang tertahan.”
“Mohon dipastikan, sebelum kiamat itu datang, bukan hanya sekedar prasangka-prasangka dalam kitab-kitab saja, “Gadis Pelangi mengubah sedikit posisi duduknya, antara lipatan-lipatan kecil ujung baju berjuntai, lanjutnya pula sambil memainkan kelembutan jemari manis, telunjuk, kelingking dan jari tengah di atas punggung telapak kekasihnya. Ada yang mengalir di antara desau itu, angin yang lewat sempat menengok kemesraan mereka. “Seperti bukan persoalan kita, tetapi ramalan demi ramalan, silih berganti datang.”
“Tenang sajalah kita, belum ada yang mengejar, bahkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain pun masih jauh dari pikiran kita.” Lelaki Atas Dirinya mencoba menahan laju pembicaraan.
“Tapi bukankah kita telah berlapis tahun melewati perjalanan ini bersama-sama, sampai saat ini, entah sampai daun yang mana lagi gugur dalam penglihatan kita.” Telapak tangan Gadis Pelangi terbuka tengadah kini berada di bawah telapak lelakinya, ada tekanan halus dan mengalir lembut, seakan getar-getar itu memberikan isyarat bahwa suasana yang mereka ciptakan merupakan tepat waktu dan tepat sasaran. Pelan lembut halus melintas.
Angin di luar tenda café sedikit nakal mempermainkan liuk-liuk pucuk dedaun. Ada banyak yang masih mampu bertahan karena akar kokohnya tak mudah tergoda oleh hempas-hempas kecil seperti sore itu.
Pagi-pagi sekali dedaun yang berserak telah dengan sigap dikumpulkan dan dikirim oleh sepasukan ibu-ibu berseragam. Pagi-pagi sekali, selintas bergerak embun pun lenyap. Waktu merangkak dalam hitungan detak ke detak yang saling berkejaran. Kejar-mengejar dalam keteraturan.
Meja-meja lain telah terpenuhi oleh tamu-tamu yang perlahan ikut menikmati suasana. Café menjelang senja tiba. Ada yang saling menyapa walau jarak memisahkan antara mereka, tetapi tidak sedikit yang memang mengosongkan kursi-kursi di lingkarannya dan lambat laun terisi dengan sangat sempurna. Mula-mula hanya duduk sendiri, kemudian datang berdua, tak lama berselang satu pengunjung hadir pula, menjadi genap empat dan saling bertatap mata. Di sudut lain sebuah meja penuh sesak sejak semula, riuh gaduh canda ria, bahkan gelombang tawa yang digelegarkan sampai jauh bergema. Suasana tetap saja terjaga. Musik perlahan mengalun, ternyata menjadi perekat dan jebak-jebak sajian agar menjadi lebih betah berlama-lama. Lagu-lagu dengan irama slowly. Lampu-lampu temaram di jalan mulai menyala. Di bawah tenda café, penerangan pun sigap membaca gejala agar gelap jangan sampai lebih dahulu menyergap. Lelaki Atas Dirinya, Gadis Pelangi, Tamu-Tamu café, beberapa orang hilir mudik membawa pesanan. Di bagian lain orang-orang cekatan mempersiapkan sajian, dengan sekat rendah maka terlihat jelas kesibukan yang dipertontonkan.
Malam sebentar lagi memeluk taman. Tak tampak lagi daun yang gugur. Semburat jingga di langit perlahan menyusup menuju lenyap. Lampu-lampu menyala sempurna, ditata dalam ruang rapi dan apik. Cahaya dari sorot lampu kendaraan berselang-seling, melibas memotong di jalan-jalan sekeliling taman.
“Baiklah. Aku akan melamarmu dalam hitungan lima hari ke depan,” ucapnya tegas.
“Sungguh. Tentu ini bukan lelucon?” balas yang diajak bicara.
“Kita akan atur bersama, bagaimana sebaiknya.”
“Sangat membahagiakan.”
Antara kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol dan seluruh bagian telapak tangan, semua menjadi satu bagian yang bermain dalam remas-remas gelora. Darah sudah tidak lagi terpisah-pisah dalam mengalirkan arusnya. Semua menjadi satu, tulang daging kulit dan perasaan. Lelaki Atas Dirinya, Gadis Pelangi adalah sepasang mahluk tuhan yang tidak begitu peduli lagi dengan pikirannya, masing-masing membenamkan perasaan mereka dalam gumpal-gumpal detak jantung yang berpacu. Cahaya mata mereka bertemu satu pandang dalam garis lurus yang seimbang. Garis yang beraturan.
Tuntutan yang saling berkejaran. Tanpa memahami bahwa detik demi detik sama dengan tarikan napas yang seharusnya dilesapkan, seharusnya diresapkan, seharusnya diselamatkan, seharusnya dileburkan, ke dalam rongga, ke dalam sepenuh ruang bernama dada, ke dalam ruang-ruang sekecil apa pun ia, pun juga pada ruang yang bernama gelembung-gelembung teramat kecil dari hasil serapan makanan yang dicerna, kemudian mengalir di pembuluh ke seluruh tubuh. Kejar-mengejar, tak mengenal lelah, tak mengenal lelap barang sekejap. Sebab, bila terlena maka akan fatal akibatnya.
Gerimis hadir perlahan. Dan biasanya hujan akan memperpanjang percakapan, walau dalam gigil kecil yang dipaksakan untuk bertahan. Satu persatu orang-orang dari dalam café beranjak pergi. Air Mancur di tengah taman itu tak lagi mengeluarkan bunyi ritmis yang memercik.
Pasca hujan. Humus merata di atas permukaan. Tanah hitam warna gembur, tanah tengadah menjanjikan. Janjikan kemakmuran di tengah perubahan cuaca yang di bulan-bulan terakhir ini terlalu sulit diperkirakan.
Sebuah kota yang memperlakukan warganya dengan kemanjaan suasana. Warga pun memanfaatkannya dengan suka cita. Ternyata suasana itu tidaklah gratis semua didapatkan, semakin eksklusif maka semakin jauh perbedaan jarak-nilai untuk mendapatkannya. Suasana yang gratis tetap tersedia, tentu di ruang-ruang publik,biasanya ruang-ruang itu terbuka.
Rasa bahagia tampak jelas terbaca di raut wajahnya. Gadis Pelangi, semakin erat dan mesra meremas jari-jemari, kekasihnya yang telah dengan terbuka mengutarakan hasrat yang dinanti-nanti. Sebuah kepastian dari perjalanan mereka.
“Engkau terlihat menangis,” seru Lelaki Atas Dirinya.
Punggung telunjuk kirinya menempel di bagian bawah kelopak mata Gadis Pelangi. Sedikit sembab dari lekuk turunan air mata yang turun perlahan.
“Ya, aku sedang berbahagia,” suaranya terbata menahan sendu.
Ingin dinikmatinya perasaan hangat yang dialirkan dari pertemuan kulit itu, dari sentuhan mesra dan penuh perhatian itu, dari romantis itu. Menikmati pernyataan yang telah didengarnya malam ini di sebuah café pada sebuah kota ketika menikmati suasana. Sejak sore hari, terlintas kembali di bayang-bayang mata selembar daun yang gugur, daun-daun itu saling mengejar satu dengan yang lain, mengejar kejatuhan mereka. Tidak pula pupus dalam ingatannya ketika angin berhembus memainkan daun-daun pohon seakan memperlihatkan betapa indahnya liuk-liuk itu sebagai tarian dari gairahnya, gairah kekasihnya. Angin pun saling kejar-mengejar, mengejar kekosongan, mengejar kehampaan. Masih mesra di belai jemarinya, kelingking mengejar jari manis mengejar jari tengah mengejar telunjuk mengejar ibu jari mereka, saling mengejar seperti darah yang mengalir, mengejar lenyap, mengejar lesap. Gerimis yang mengejar menuju hujan, dan hujan menutup kesempatan untuk beranjak, tetapi waktu itu adalah bagian terpenting yang pernah ia dengar dari banyaknya suara dan ucapan-ucapan. “Aku akan segera menjadi mempelai.”
Tentu saja tidak akan berhenti pada satu titik karena semua pemberhentian adalah jeda di sepanjang jarak perjalanan.
Posko Budaya Mingguraya, 24 Desember 2010
Jumat, 25 Maret 2011
Selintas. Selembar daun gugur.
 11.07
11.07
 Nathan
Nathan




















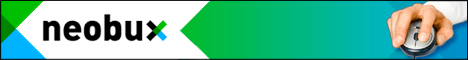


0 komentar:
Posting Komentar