Ronggeng Dukuh Paruk (RDP) merupakan salah satu novel trilogi karya Ahmad Tohari, selain Jentera Bianglala dan Lintang Kemukus Dini Hari. Banyak pengamat bilang, RDP merupakan satu di antara sekian novel Indonesia mutakhir yang sangat kuat warna lokalnya. Ia menampilkan sisi-sisi kearifan lokal masyarakat desa yang masih sangat kental persentuhannya dengan alam. Gaya naratif Kang Tohari, demikian novelis yang tetap betah dan nyaman tinggal di kampung kelahirannya, desa Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah itu biasa disapa, agaknya sangat tepat mendeskripsikan keakraban masyarakat dukuh Paruk terhadap berbagai fenomena alam yang terjadi di sekelilingnya. Sangat beralasan apabila novel yang “eksotis” ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing.
RDPRDP tak bisa dilepaskan dari peran seorang Srintil yang dinilai mampu menggeliatkan semangat dukuh Paruk yang kecil, miskin, terpencil, dan bersahaja. Pamornya makin cemerlang setelah ia dinobatkan menjadi seorang ronggeng. Konon, tanpa Srintil, dukuh Paruk akan merasa kehilangan jatidiri. Srintil mendadak menjadi tokoh yang amat terkenal dan digandrungi. Cantik dan menggoda. Semua penduduk dari berbagai lapisan usia merasa memiliki ronggeng itu.
Namun, malapetaka politik tahun 1965 membuat dukuh Paruk hancur, baik secara fisik maupun mental. Karena kebodohannya, mereka terbawa arus dan divonis sebagai manusia-manusia yang telah mengguncangkan negara ini. Pedukuhan itu dibakar. Ronggeng beserta para penabuh calungnya ditahan. Hanya karena kecantikannyalah Srintil tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh para penguasa di penjara itu. Akan tetapi, pengalaman pahit sebagai tahanan politik membuat Srintil sadar akan harkatnya sebagai manusia. Oleh karena itu setelah bebas, ia berniat memperbaiki citra dirinya. Ia tak ingin lagi melayani lelaki mana pun. Ia ingin menjadi wanita somahan. Dan ketika Rasus muncul dalam hidupnya, sepercik harapan timbul, harapan yang makin lama makin membuncah. Tapi, ternyata Srintil kembali terempas, kali ini bahkan membuat jiwanya hancur berantakan, tanpa harkat secuil pun.
Salah satu bagian yang menarik dalam RDP adalah deskripsi tentang prosesi “sakral” penahbisan Srintil sebagai ronggeng. Konon, untuk menjadi seorang ronggeng, Srintil harus melewati proses penobatan yang terkesan sakral dan mistis. Selain harus melakukan pemandian di pekuburan Ki Secamenggala, sesepuh yang dianggap sebagai “cikal bakal” dukuh Paruk, dia harus menjalani upacara bukak klambu; sebuah ritual sayembara “penyerahan” keperawanan kepada seorang lelaki. Berikut ini kutipannya.
Aku mengira upacara permandian di pekuburan itu adalah syarat terakhir sebelum seorang gadis sah menjadi ronggeng. Ternyata aku salah. Orang-orang Dukuh Paruk mengatakan bahwa Srintil masih harus menyelesaikan satu syarat lagi. Sebelum hal itu terlaksana, Srintil tak mungkin naik pentas dengan memungut bayaran.
Dari orang-orang Dukuh Paruk pula aku tahu syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh Srintil bernama bukak-klambu. Berdiri bulu kudukku setelah mengetahui macam apa persyaratan itu. Bukak-klambu adalah semacam sayembara, terbuka bagi laki-laki mana pun. Yang disayembarakan adalah keperawanan calon ronggeng. Laki-laki yang dapat menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh dukun ronggeng, berhak menikmati virginitas itu.
“Keperawanan Srintil disayembarakan. Bajingan! Bajul buntung!” pikirku.
Aku bukan hanya cemburu. Bukan pula sakit hati karena aku tidak mungkin memenangkan sayembara akibat kemelaratanku serta usiaku yang baru empat belas tahun. Lebih dari itu. Memang Srintil telah dilahirkan untuk menjadi ronggeng, perempuan milik semua laki-laki. Tetapi mendengar keperawanannya disayembarakan, hatiku panas bukan main. Celaka lagi, bukak-klambu yang harus dialami oleh Srintil sudah merupakan hukum pasti di Dukuh Paruk. Siapa pun tak bisa mengubahnya, apa pula aku yang bernama Rasus. Jadi dengan perasaan perih aku hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi.
Jauh-jauh hari Kartareja sudah menentukan malam hari Srintil harus kehilangan keperawanannya. Untuk itu Kartareja sendiri harus mengeluarkan biaya. Tiga ekor kambing telah dijualnya ke pasar. Dengan uang hasil penjualan itu dibelinya sebuah tempat tidur baru, lengkap dengan kasur bantal dan kelambu. Dalam tempat tidur ini kelak Srintil akan diwisuda oleh laki-laki yang memenangkan sayembara.
Sementara waktu suara calung lenyap dari Dukuh Paruk. Kartareja sedang giat membuat persiapan pelaksanaan malam bukak-klambu itu. Dukun ronggeng itu rajin keluar Dukuh Paruk untuk menyebarkan berita. Hanya dalam beberapa hari telah tersiar kabar tentang malam bukak-klambu bagi ronggeng Srintil. Orang-orang segera tahu pula, Kartareja menentukan syarat sekeping uang ringgit emas bagi laki-laki yang ingin menjadi pemenang.
Ya, ya, sebuah ritual yang unik. Konon, ritual semacam itu dulu benar-benar sebuah peristiwa riil. Namun, lantaran dianggap kurang manusiawi, upacara penahbisan ronggeng melalui prosesi semacam itu akhirnya dilarang. Tiba-tiba saja, saya ingat seni pertunjukan rakyat yang ada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yakni tayub yang melibatkan ledhek sebagai “pemeran utama”, yang hingga kini masih eksis. Tayub Grobogan bisa dengan mudah disaksikan ketika ada warga yang punya hajat, entah itu khitan, nikah, selapanan bayi, atau hajat nazar yang lain.
Berbeda dengan ronggeng banyumasan sebagaimana yang tergambar dalam RDP, ledhek di Grobogan diterjuni oleh para pelakunya tanpa harus melalui ritual khusus yang bersifat mistis. Seperti layaknya profesi hiburan yang lain, ledhek diterjuni secara wajar-wajar saja oleh para pelakunya. Asal ada niat dan sanggup, meluncurlah mereka ke tengah-tengah masyarakat sebagai ledhek.
ledhekLedhek, konon merupakan jarwa-dhosok dari “Elek ben angger gelem medhek-medhek” (biar jelek asal mau mendekat). Seperti kebanyakan ledhek di daerah Kabupaten Grobogan, modal kecantikan agaknya tak begitu penting, meski juga berpengaruh dalam hal pemasaran. Modalnya cukup dengan dandanan yang seronok dengan vokal yang lancar selama semalam suntuk ditambah dengan keberanian mendekati kaum lelaki.
ledhekSebagai seni pertunjukan rakyat yang bercorak agraris, konon, dulu seni tayub hanyalah sebuah tontonan perlengkapan seremoni nazar bagi warga desa yang kebetulan punya uni alias nazar. Masyarakat Grobogan meyakini adanya mitos, jika pernah punya nazar, tetapi tidak segera dilaksanakan setelah niatnya tercapai, maka yang bersangkutan akan dirundung malapetaka. Misalnya, ada anggota keluarga yang sakit parah, bahkan sampai meninggal dunia atau dapat pula berubah musibah fatal yang lain. Sebagai medium pengabulan nazar, diundanglah ledhek untuk menolak musibah yang bakal datang. Selain itu, juga sebagai pengucapan rasa syukur kepada Hyang Widhi atas niat dan maksudnya yang telah terkabul. Lama pertunjukan cukup singkat sekitar 1-2 jam. Konon, mantra-mantra yang diucapkan sang ledhek itulah yang sanggup meredam segala musibah.
Dengan iringan gamelan yang mengalun, sang ledhek mulai mengucapkan matra dalam bentuk tembang. Ada suasana sakral di sana. Di tengah asap dupa yang membubung dengan segenap uba rapenya semacam ayam panggang, keris, onggokan pisang, ketupat, dan beras putih, sang ledhek tak henti-hentinya mengucapkan mantra sambil menyebar beras putih ke segala penjuru sebagai tulak balak: “…ana sengkala saka kulon tinulak bali mangulon. Sing nulak balak Raja Iman Slamet …” (ada musibah dari barat ditolak kembali ke barat. Yang menolak Raja Iman Selamat) ….” Byur! Beras putih disebar ke arah barat. Demikian seterusnya higga tujuh kali sesuai dengan arah yang disebutkan. Setelah sang ledhek selesai mengucapkan mantra dalam bentuk tembang, tamatlah pertunjukan sebagai pertanda bahwa nazar telah dilaksanakan. Mereka yakin, musibah tak mungkin muncul sekaligus sang empunya nazar terhindari dari segala petaka.
Namun, seirama dengan perkembangan seni hiburan di daerah pelosok pedesaan, seni tayub kini berubah fungsi, suasana, dan temponya. Dari fungsinya sebagai perlengkapan seremonial nazar, kini beralih fungsi sebagai hiburan semata. Suasana sakral pun sirna, berganti suasana ingar-bingar di tengah musik gamelan yang membubung ditingkah ketipak kendang yang keras membentak. Tempo pertunjukannya pun berlangsung semalam suntuk alias byar klekar seperti hiburan lain pada umumnya.
Seni pertunjukan rakyat berbau hiburan agaknya akan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya agar tetap bisa eksis di tengah gempuran budaya global. Meski secara ritual, antara RDP dan Tayub Grobogan mengalami prosesi yang berbeda, tetapi secara kultural, seni pertunjukan rakyat ini memiliki fungsi yang (nyaris) sama, yakni sebagai klangenan (hiburan) masyarakat agraris di tengah-tengah rutinitas keseharian. Mungkin ada benarnya kalau ada orang yang bilang bahwa pada dasarnya setiap masyarakat memiliki naluri untuk menemukan katharsis dan pencerahan jiwa melalui seni pertunjukan yang dianggap mampu memenuhi hasrat emosi dan spiritualnya. Begitukah? ***
Sabtu, 26 Maret 2011
Antara Ronggeng Dukuh Paruk dan Tayub Grobogan
 03.55
03.55
 Nathan
Nathan




















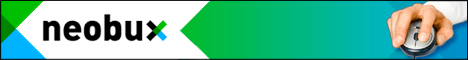


0 komentar:
Posting Komentar